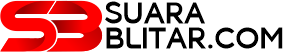Pelaksanaan Reforma Agraria Menjadi Sorotan Menjelang Hari Tani Nasional
Menjelang Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September, pelaksanaan reforma agraria di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan tantangan signifikan. Dengan hampir satu tahun berkuasa, pemerintah dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah dalam implementasi kebijakan ini, yang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi petani.
Sejak masa pemerintahan sebelumnya, program reforma agraria sering kali diiringi dengan momen ceremonial, seperti pembagian sertifikat tanah oleh presiden. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, antara 2015 hingga 2023 telah dibagikan sekitar 10,3 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Meskipun langkah ini mendapat kritik karena dianggap lebih fokus pada legalisasi aset dibandingkan redistribusi yang substansial, bagi banyak pihak, ini tetap menjadi simbol kehadiran negara dalam mendukung isu agraria.
Saat ini, urgensi reforma agraria semakin meningkat dengan adanya dua tantangan besar: deindustrialisasi dini dan proses deagrarianisasi yang berlangsung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan signifikan, dari puncaknya sekitar 32 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 18,7 persen pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini menjadi alarm bagi ketahanan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor industri stagnan, hanya tumbuh rata-rata 1,2 persen per tahun dalam dekade terakhir.
Di sisi lain, deagrarianisasi di Indonesia ditandai oleh tiga gejala penting. Pertama, ketergantungan yang semakin kuat terhadap impor pangan, dengan nilai impor pangan Indonesia mencapai 28,5 miliar dolar AS pada tahun 2023. Kedua, mayoritas petani di Indonesia terhimpit dalam kondisi lahan yang sempit; data menunjukkan bahwa 56 persen petani memiliki lahan di bawah 0,5 hektare. Ketiga, lemahnya regenerasi petani, di mana hanya 27 persen petani muda yang masih aktif di sektor pertanian, mengindikasikan tidak menariknya kehidupan di bidang tersebut.
Untuk menanggapi deindustrialisasi, pemerintah meluncurkan kebijakan hilirisasi di sektor sumber daya alam, seperti minerba, perkebunan, dan perikanan. Namun, program ini belum mampu menghubungkan antara hilirisasi dan agenda reforma agraria. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa investasi hilirisasi minerba mencapai 15,3 miliar dolar AS pada tahun 2023, tetapi tidak menyumbang pada peningkatan kepemilikan rakyat atas usaha dan lahan di sekitarnya.
Sebaliknya, model hilirisasi yang ada justru memicu konflik agraria baru dan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, pelaksanaan reforma agraria yang komprehensif dan terintegrasi menjadi semakin mendesak agar dapat menjawab tantangan yang dihadapi sektor agraria dan perekonomian nasional.
Dengan semakin nyata ancaman deindustrialisasi dan deagrarianisasi, reforma agraria bukan sekadar agenda kebijakan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih serius dalam merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan dan memastikan bahwa tanah merupakan sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.