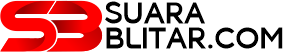Ada sesuatu yang ironis dalam cerita tentang Monsanto. Ia bermula dari sebuah percobaan sederhana seorang ayah yang ingin membasmi tanaman pengganggu agar anak-anaknya tidak gatal, lalu berakhir sebagai salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah industri modern. Dari sebotol herbisida yang menjanjikan efisiensi, lahir sebuah kerajaan yang mengatur cara umat manusia bercocok tanam, memengaruhi kesehatan, dan bahkan meracuni hubungan antara sains dan kepercayaan publik. Yang menarik bukan hanya keberhasilan Monsanto dalam menanamkan pengaruhnya, melainkan bagaimana perjalanan itu mengilustrasikan nafsu manusia untuk mengendalikan alam sekaligus ketakutan kolektif kita terhadap dampak dari kendali tersebut.
Awalnya, semua tampak sederhana. Di pertengahan abad ke-20, para ilmuwan menemukan bahwa hormon tumbuhan tertentu bisa memaksa gulma tumbuh begitu cepat hingga akhirnya mati sendiri. Inilah 2,4-D, cikal bakal herbisida modern. Ia dipuji sebagai penyelamat petani dari pekerjaan kotor menyiangi ladang dengan tangan, juga sebagai alternatif “lebih manusiawi” dibanding arsenik atau bahan beracun lain yang kala itu lazim dipakai. Monsanto segera masuk ke dalam bisnis ini, bukan hanya menjual bahan kimia, tetapi menjual mimpi efisiensi pertanian yang seakan bebas risiko.
Namun seperti semua mimpi industri, kenyataan tidak pernah seindah brosur. Pabrik Monsanto di Nitro, West Virginia, meledak pada 1949. Awan hitam naik ke udara, debu beracun turun pelan-pelan menutupi kota. Para pekerja jatuh sakit, kulit mereka melepuh, tubuh mereka mengeluarkan bau kimia. Bertahun-tahun kemudian baru diketahui penyebabnya: dioxin, zat sampingan yang lahir ketika suhu reaksi kimia terlalu tinggi. Para dokter di Jerman sudah memperingatkan sejak 1950-an, tetapi perusahaan memilih bungkam. Mereka lebih takut kehilangan pasar ketimbang kehilangan pekerja.
Puncak tragedi terjadi saat perang Vietnam. Monsanto bersama Dow Chemical memasok Agent Orange, campuran 2,4-D dan 2,4,5-T, untuk menyemprot hutan-hutan tropis. Dengan logika militer, alam harus tunduk. Dengan logika industri, kontrak harus dipenuhi. Jutaan liter disebarkan ke tanah dan manusia. Tentara, petani, perempuan, anak-anak, semua terkena. Laporan medis kemudian mencatat kanker, cacat lahir, kerusakan sistem kekebalan. Seakan-akan tubuh manusia hanyalah percobaan laboratorium raksasa. Perusahaan tentu punya arsip surat-menyurat yang menunjukkan mereka tahu risiko itu. Tetapi kata “tahu” tidak berarti “mengakui.”
Ironisnya, justru di saat bayang-bayang Agent Orange masih membekas, Monsanto menemukan senjata kimia baru yang lebih “bersih.” Glyphosate, atau yang dijual dengan nama Roundup, diluncurkan pada 1974. Ia menghantam gulma dengan mekanisme biologis cerdik: memutus jalur pembentukan asam amino yang hanya ada pada tumbuhan. Karena manusia tak memiliki jalur itu, Monsanto mengeklaim Roundup “lebih aman daripada garam dapur.” Para petani menyambut dengan antusias, karena untuk pertama kalinya, ladang bisa diperlakukan seperti kanvas kosong. Cukup semprot, dan semua tanaman liar lenyap.
Namun di balik kegemilangan Roundup, tersimpan sebuah strategi bisnis yang jauh lebih ambisius. Monsanto tidak puas menjual botol herbisida; mereka ingin menjual seluruh ekosistem pertanian. Dari situlah lahir “Roundup Ready” – benih jagung, kedelai, atau kapas yang telah direkayasa agar tahan glyphosate. Petani tak bisa menanam ulang biji hasil panen, karena kontrak melarangnya. Mereka bahkan tak boleh berbagi benih dengan tetangga. Monsanto menyewa penyelidik swasta, menyisir ladang dengan helikopter, menuntut petani yang dicurigai melanggar. Satu perusahaan menjadi polisi, hakim, sekaligus pemilik lahan virtual.
Di sini terlihat wajah baru monopoli: bukan lagi menguasai pabrik atau pasar, melainkan menguasai genetika kehidupan. Biji-bijian, yang selama ribuan tahun diwariskan dari tangan ke tangan, tiba-tiba berubah menjadi properti berlisensi. Dari perspektif psikologis, ini menimbulkan rasa ketidakberdayaan kolektif. Petani yang dulu merasa bagian dari rantai panjang tradisi agraris, kini terpaksa menjadi konsumen tetap dalam siklus utang-benih-herbisida. Ia bukan lagi pencipta pangan, melainkan pelanggan yang tunduk pada kontrak hukum.
Sementara itu, dunia akademik menjadi ajang tarik menarik antara kebenaran ilmiah dan kepentingan industri. Pada 2015, Badan Internasional Penelitian Kanker (IARC) menyatakan glyphosate “mungkin karsinogenik.” Geger pun terjadi. Monsanto buru-buru mengeluarkan bantahan, mengutip penelitian yang menyatakan Roundup aman. Tetapi gugatan hukum mulai bermunculan. Pengacara menggali dokumen internal yang kemudian dikenal sebagai “Monsanto Papers.” Dari situ terbukti betapa dalamnya perusahaan mencampuri ranah ilmiah: menulis ulang laporan, mendanai penelitian yang seolah independen, bahkan menekan regulator agar melunakkan bahasa teknis.
Salah satu kisah yang mengguncang publik adalah kasus Dewayne Johnson, seorang petugas kebersihan sekolah yang kerap menyemprot Roundup. Ia didiagnosis mengidap limfoma non-Hodgkin. Di pengadilan, juri memutuskan Monsanto bersalah, dan Johnson mendapat ganti rugi ratusan juta dolar. Meski angka itu kemudian dikurangi, simbolisme kasus ini jauh lebih besar: untuk pertama kalinya narasi “aman” yang dipelihara perusahaan retak di hadapan juri awam.
Pada titik inilah sejarah Monsanto berubah arah. Bayer, raksasa farmasi asal Jerman, membeli Monsanto pada 2018. Langkah yang semula dianggap strategis berubah menjadi mimpi buruk, karena bersamaan dengan itu ribuan gugatan hukum membanjiri pengadilan. Bayer akhirnya harus merogoh belasan miliar dolar untuk menyelesaikan perkara. Nama Monsanto dihapus dari papan nama perusahaan, seolah sejarah bisa dihapus dengan tip-ex korporat. Tetapi ingatan publik tak mudah disulap.
Kini, bahkan tanpa bayangan pengadilan, Roundup menghadapi musuh baru: evolusi. Puluhan spesies gulma di berbagai negara telah mengembangkan resistansi terhadap glyphosate. Petani kembali dipaksa mencampur herbisida lama yang lebih berbahaya, atau mencari solusi mekanis yang justru dihindari generasi sebelumnya. Dengan kata lain, siklus dominasi kimia berulang: satu zat datang sebagai penyelamat, lalu mengundang bencana, lalu diganti zat lain dengan janji serupa.
Dari kacamata filsafat, kisah Monsanto lebih mirip tragedi Yunani ketimbang sekadar kronik bisnis. Ada hubris: keyakinan bahwa manusia bisa menundukkan alam dengan formulasi kimia. Ada nemesis: perlawanan alam dalam bentuk gulma kebal, penyakit, dan gugatan hukum. Dan ada katarsis: kesadaran pahit bahwa inovasi tanpa etika hanya mempercepat kehancuran.
Namun tidak adil bila kita hanya menuding Monsanto seolah ia monster tunggal. Ia adalah produk dari sebuah sistem yang memuja efisiensi, mengejar pertumbuhan tanpa henti, dan menganggap petani serta konsumen sebagai pasar belaka. Setiap kali kita membeli produk murah dari rak supermarket, kita ikut menyiram ladang Monsanto secara tidak langsung. Kita menikmati buah dari sistem yang kita kritik.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Monsanto jahat atau tidak, melainkan apakah kita siap hidup dengan konsekuensi logika yang sama: logika yang menukar kompleksitas ekosistem dengan keseragaman, logika yang mendefinisikan pangan sebagai komoditas, bukan sebagai hubungan antara manusia dan tanah.
Barangkali, yang paling perlu kita renungkan adalah bagaimana sains digunakan bukan sebagai cahaya, tetapi sebagai tirai. Data bisa disusun untuk menghibur investor, jurnal bisa disusun ulang untuk menenangkan regulator, dan publikasi bisa diatur untuk membentuk opini. Jika kebenaran ilmiah dapat dibeli, apa yang tersisa dari otoritas sains? Seorang filsuf kontemporer pernah menulis bahwa manusia modern lebih takut pada ketidakpastian daripada pada bahaya itu sendiri. Monsanto paham betul psikologi ini. Mereka menjual kepastian dalam bentuk benih steril dan botol herbisida, meski harga sebenarnya adalah ketidakpastian jangka panjang yang jauh lebih besar.
Kisah Monsanto seharusnya menjadi pengingat. Bahwa teknologi pertanian tidak pernah netral. Bahwa perusahaan bukan hanya penyedia solusi, melainkan juga pembentuk masalah. Bahwa setiap kali kita menuntut efisiensi, ada biaya tersembunyi yang dibayar oleh tubuh manusia, tanah, dan generasi mendatang.
Mungkin inilah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman: apakah kita ingin dunia yang lebih sederhana tapi lebih rapuh, atau dunia yang lebih beragam namun lebih sulit dikendalikan? Pertanyaan itu bukan hanya milik petani atau regulator, melainkan milik semua orang yang makan, yang artinya milik kita semua.
Monsanto memang sudah tiada sebagai nama, tetapi warisannya tetap hidup. Ia hidup di benih yang ditanam, di tanah yang disemprot, di tubuh yang sakit, dan di wacana publik yang penuh ketidakpercayaan terhadap sains. Sejarah ini tidak bisa dibatalkan, tetapi bisa dijadikan cermin. Pertanyaannya, beranikah kita menatapnya?