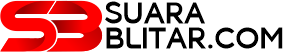Pagi hari, truk-truk pengangkut tebu merayap di jalanan pedesaan Blitar. Di banyak titik, hamparan batang tebu yang siap panen tampak kehijauan. Namun, kabar baik dari ladang tidak selalu berlanjut di pabrik. Gudang gula penuh, antrean truk mengular, dan telepon dari tengkulak makin jarang berbunyi.
“Gula sudah numpuk,” keluh seorang sopir truk yang menepi di tepi jalan. Ungkapan “sudah numpuk” menjadi kunci dari keresahan musim ini.
Secara agronomis, Blitar merupakan salah satu sentra produksi tebu yang penting. Berdasarkan data per 3 Agustus 2024, luas areal tebu di Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 8.900 hektare dengan produksi sekitar 655 ribu ton tebu. Angka ini menegaskan peran tebu sebagai salah satu tulang punggung perkebunan setempat.
Di hilir, PT Rejoso Manis Indo (RMI), pabrik gula di Blitar, mencatatkan capaian signifikan pada musim giling 2024, yaitu produksi 100.201 ton gula dari 1.113.419 ton tebu yang digiling selama 149 hari. Manajemen RMI menyatakan kepatuhan pada harga acuan pembelian (HAP) gula di tingkat petani sebesar Rp14.500/kg dan menyerap tebu petani sesuai kebijakan pemerintah.
Memasuki musim 2025, RMI bahkan menargetkan kapasitas giling 1,5 juta ton tebu, mengindikasikan kesiapan industri gula Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar juga menekankan bahwa luas perkebunan di wilayah ini mencapai 29 ribu hektare, dengan tebu sebagai komoditas kunci. Di atas kertas, ekosistem tebu Blitar bekerja dengan baik: lahan tumbuh, pabrik menggiling, dan produk jadi tersedia. Namun, di lapangan, hubungan antara kebun, pabrik, dan pasar terhambat akibat kebijakan dan masuknya barang dari luar yang mengubah kurva penawaran-permintaan.
Kondisi Nasional dan Dampaknya terhadap Petani
Secara nasional, tahun 2025 justru ditandai oleh kabar “baik” yang terasa getir bagi petani. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan surplus gula konsumsi sekitar 1,1 juta ton pada Agustus 2025. Pemerintah juga menargetkan produksi gula konsumsi mencapai sekitar 2,6 juta ton pada periode 2024/2025, yang disebut sebagai level tertinggi kedua di ASEAN setelah Thailand.
Jawa Timur tetap menjadi episentrum gula nasional. Data pemerintah menunjukkan Jatim menyumbang sekitar 50–52 persen produksi gula Indonesia. Pada tahun 2024, Jatim menghasilkan sekitar 1,28 juta ton gula dari sekitar 16,7 juta ton tebu, dengan rendemen rata-rata 7,6 persen. Dengan kebutuhan gula Jatim sekitar 281 ribu ton per tahun, provinsi ini secara matematis surplus hampir 1 juta ton.
Namun, di tengah narasi surplus, pada awal 2025 pemerintah memberikan penugasan impor gula (terutama gula mentah/raw sugar) hingga 200 ribu ton. Alasan yang diberikan adalah untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan menjaga pasokan menjelang periode konsumsi tinggi (Ramadan dan Idul Fitri). Pejabat Bapanas menegaskan bahwa impor bukan karena kekurangan produksi, melainkan untuk menambah cadangan dan menstabilkan pasokan.
Secara makro, alasan “cadangan” bisa diterima. Namun, di hilir, impor—terutama jika waktu dan pengawasan distribusinya kurang presisi—berpotensi menekan harga dan memperlambat penyerapan gula petani. Akibatnya, barang tersedia, tetapi arus kas yang menjadi “oksigen” bagi petani justru tersendat.
Masalah di Lapangan
Di lapangan, khususnya di Jawa Timur sebagai sentra tebu, puluhan ribu ton gula petani tidak terserap. Pada beberapa pekan di Agustus 2025, asosiasi petani berkali-kali menyuarakan bahwa 76.700 ton gula petani di wilayah kerja BUMN gula belum terserap, membuat sejumlah pabrik mengurangi laju giling karena gudang penuh.
Berbagai pemberitaan nasional mengonfirmasi akumulasi stok sekitar 100 ribu ton gula yang mandek di gudang pabrik dan milik petani. Pemerintah merespons dengan skema penyerapan senilai Rp1,5 triliun melalui BUMN pangan untuk membeli gula petani. Namun, di lapangan, petani mengeluh proses administrasinya lambat, sementara beban biaya operasional terus berjalan.
Selain masalah stok, petani juga menuding rembesan gula rafinasi (yang seharusnya hanya untuk industri) masuk ke pasar konsumsi, sehingga menekan harga gula petani dan melemahkan daya serap pasar. Bapanas sendiri sempat menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap masalah ini.
Dampak Finansial dan Permasalahan Harga
Secara teknis, laju di kebun terjaga, dan pabrik seperti RMI menunjukkan kinerja produksi yang besar pada 2024. Namun, jika pasar konsumsi tersumbat karena stok melimpah dan impor yang menambah pasokan, arus pembayaran ke petani ikut melambat.
Petani menyerahkan tebu ke pabrik selama musim giling (4–5 bulan) dan menunggu pembayaran dari hasil penjualan gula. Jika gula tidak keluar atau keluar dengan harga di bawah acuan, maka biaya kebun untuk musim berikutnya—seperti pupuk, upah tebang-angkut, sewa lahan, dan pembibitan—tidak tertutup. Inilah alasan keluhan seperti “kami sulit meneruskan tebang angkut” dan “beberapa pabrik gula sudah mengerem giling karena gudang penuh” berulang kali terdengar di lapangan sepanjang Agustus 2025.
Harga Acuan Pembelian (HAP) gula petani ditetapkan Rp14.500/kg untuk menjaga keekonomian petani. Namun, ketika gula petani ditawar di bawah angka ini, potensi margin langsung habis atau bahkan berubah menjadi rugi. Laporan lapangan menunjukkan harga sering turun saat stok menumpuk dan ketika ada kompetisi tidak seimbang dengan gula rafinasi yang salah jalur.
Di hulu, harga tebu (bahan baku) juga bergejolak. Beberapa pekan terakhir, harga tebu di sebagian sentra Jatim sempat turun ke kisaran Rp79.000 per kuintal (Rp790.000/ton) dari posisi sekitar Rp89.000 per kuintal. Penurunan ini tidak lazim dibandingkan pola musim-musim sebelumnya ketika harga cenderung naik menjelang akhir giling.
Secara matematis, ekonomi tebu Blitar memiliki potensi besar. Ambil contoh data 2024: RMI memproduksi 100.201 ton gula dari 1,113 juta ton tebu. Jika seluruh gula terserap sesuai HAP Rp14.500/kg, nilai kotornya mendekati Rp1,45 triliun. Angka ini belum termasuk nilai dari tetes (molasses) dan ampas (bagasse) yang memiliki nilai industri. Setiap penurunan harga atau keterlambatan serapan berarti ada potensi nilai ekonomi yang tertahan, yang seharusnya berputar di tangan petani, buruh, sopir, dan pelaku ekonomi lainnya.
Tiga Penyebab Utama Surplus Gula dan Dampak Ekonominya
Waktu dan Kuota Impor: Impor untuk cadangan memiliki justifikasi, tetapi waktunya di awal panen memunculkan kesan “banjir pasokan” yang kontraproduktif bagi penyerapan gula petani. Pernyataan resmi menegaskan impor 200 ribu ton untuk cadangan, tetapi di hilir, bukti keterlambatan serapan dan stok menumpuk menunjukkan adanya masalah.
Rembesan Gula Rafinasi ke Pasar Konsumsi: Asosiasi petani berulang kali menuding gula rafinasi yang seharusnya hanya untuk industri merembes ke pasar konsumsi rumah tangga, memukul harga gula petani.
Keterbatasan Ruang dan Keuangan Pabrik Gula: Ketika gudang penuh dan pembiayaan pembelian gula petani tersendat, laju giling ikut terkendala. Hal ini menciptakan lingkaran setan: tebu mengantri di luar, gula mengantri di dalam.
Usulan Solusi Kebijakan
Ketika gula tidak terserap, petani tidak menerima pembayaran tepat waktu. Mereka menyebut diri “gagal panen secara finansial.” Ancaman mogok massal dari kelompok petani tebu Jatim pada pertengahan Agustus 2025 menjadi sinyal seriusnya persoalan ini. Petani mendesak realisasi anggaran Rp1,5 triliun yang dijanjikan pemerintah untuk menyerap gula petani.
Berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan kebijakan:
- Kunci Rembesan Gula Rafinasi: Perlu penegakan dan pengawasan ketat agar gula rafinasi hanya disalurkan ke industri. Ketika “rembesan” ini ditutup, ruang pasar untuk gula petani akan membesar.
- Sinkronkan Waktu Impor dengan Kalender Giling: Impor untuk cadangan sebaiknya tidak memengaruhi harga spot pada puncak panen. Penyaluran bisa dilakukan secara bertahap setelah puncak giling, sambil tetap menjaga HAP di tingkat petani.
- Percepat Realisasi Dana Penyerapan: Janji Rp1,5 triliun harus segera direalisasikan. Skema pembelian oleh BUMN pangan harus diproses cepat dan terukur dampaknya, dengan prioritas pada daerah sentra yang stoknya paling menumpuk.
- Manajemen Gudang dan Logistik Berbasis Data: Optimalisasi “penyangga” regional di bawah BUMN pangan dapat membantu. Data harian perlu dibuka untuk menghindari hambatan (bottleneck) yang menyebabkan truk tebu mengular.
- Perjanjian Hilirisasi: Tetes dan Etanol sebagai Penyelamat Arus Kas: Harga tetes (molasses) dan etanol dapat menjadi katup pelepas ekonomi petani. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan agar produk samping tebu tidak kalah bersaing oleh regulasi impor yang terlalu “ramah.”
- Perbaiki Kontrak dan Skema Pembayaran antara Petani–Pabrik: Perlu didorong kontrak yang lebih adil—misalnya price floor berbasis HAP, dengan mekanisme talangan (bridging finance) dari lembaga pembiayaan pangan agar petani tidak terpaksa menjual dengan harga murah demi arus kas harian.
Kesimpulan
Di Blitar, luas areal tebu lebih dari 8.900 ha dan volume produksi di atas 650 ribu ton pada 2024 menunjukkan basis ekonomi riil yang kuat. Pabrik seperti RMI juga menunjukkan kapasitas hilir yang siap bekerja. Namun, jika pasar konsumsi tersumbat, arus pembayaran ke petani akan melambat.
Jika masalah penyerapan ini tidak segera diselesaikan, sinyal-sinyal darurat sosial akan semakin keras: ancaman mogok, stok 100 ribu ton yang tidak laku, harga tebu yang merosot, dan biaya kebun yang tidak tertutup. Pada titik ini, bukan hanya misi swasembada gula yang mundur, tetapi juga kepercayaan petani yang retak—sesuatu yang jauh lebih sulit diperbaiki.
Fenomena ini mengajarkan paradoks sederhana: melimpah tidak selalu berarti sejahtera. Di Blitar, di Jatim, dan di banyak sentra tebu lain, melimpah justru bisa berarti mandek jika cadangan tidak diatur, jika arus impor tidak sinkron dengan giling, dan jika pengawasan distribusi setengah hati. Solusinya bukan memilih antara impor atau produksi dalam negeri, melainkan sinkronisasi.
Kita perlu memastikan impor yang dibutuhkan datang pada waktu yang tidak mematahkan harga petani; memastikan cadangan pemerintah berperan sebagai penyeimbang, bukan pesaing; menutup rembesan rafinasi; mempercepat pembelian pemerintah pada HAP Rp14.500/kg; dan membuka data agar setiap truk tebu yang melintas di jalanan Blitar tidak lagi bertanya “gula ke mana,” melainkan melaju ke gudang yang pasti menyerap dan pasti membayar. Jika ini dikerjakan dengan tegas, cepat, dan konsisten, maka kalimat “gula sudah numpuk” akan hilang dari percakapan warung di tepi jalan. Yang tersisa adalah lahan yang terus ditanami, pabrik yang terus menggiling, dan rumah-rumah petani yang kembali pasti arus uangnya. Dengan demikian, swasembada akan berhenti menjadi kata-kata, dan berubah menjadi realitas yang dirasakan sampai ke kantong petani.