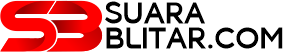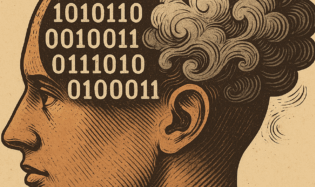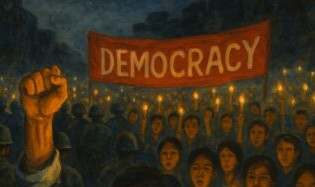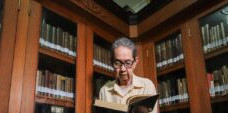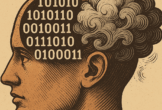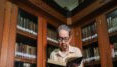Dalam sepuluh tahun terakhir, nama Jensen Huang tak sekadar menempati barisan tokoh teknologi. Ia telah menjadi wajah yang akrab dalam pembicaraan tentang arah peradaban digital. Sebagai pendiri sekaligus pemimpin Nvidia, Huang tak hanya merancang perangkat keras, tetapi juga turut menggeser arah pemikiran kolektif tentang masa depan kecerdasan buatan. Salah satu pemikirannya yang belakangan kerap dibicarakan ialah ajakannya agar anak-anak muda mempertimbangkan jurusan fisika, alih-alih sepenuhnya mengejar ilmu komputer dan pemrograman.
Pernyataan ini lahir bukan dari kegelisahan pribadi semata, melainkan dari pengamatan panjang atas arah gerak teknologi yang ia bagi menjadi tiga gelombang. Huang menyebut gelombang pertama sebagai “AI digital”. Inilah fase ketika komputer belajar mengenali gambar, mendengar suara, membaca tulisan, lalu menyusunnya menjadi keputusan—seperti wajah yang dikenali kamera, atau saran lagu yang ditawarkan oleh algoritma. Fase ini bertumpu pada mesin pembelajar, pada barisan kode, dan pada komputasi paralel yang digerakkan oleh GPU—jantung dari bisnis Nvidia. Ilmu komputer, pada masa itu, adalah jembatan utama untuk menaklukkan dunia digital.
Namun waktu berjalan, dan jembatan itu ternyata bukan satu-satunya jalan. Gelombang kedua datang, dan disebut Huang sebagai “AI generatif”. Dalam tahap ini, mesin tak sekadar menganalisis, melainkan juga mencipta. Ia menulis paragraf, melukis lanskap, membuat kode, menyusun melodi. Kemampuan ini tidak lagi menuntut manusia untuk mahir menulis perintah dalam bahasa pemrograman. Cukup berikan instruksi dalam bahasa sehari-hari—AI akan memahami, merespons, dan mencipta atas dasar itu. Apa yang dulu dianggap istimewa kini bisa dilakoni mesin dalam hitungan detik. Dalam situasi ini, Huang melihat menurunnya keunggulan kompetitif dari kemampuan coding manual.
Namun pandangannya tidak berhenti di situ. Ada gelombang ketiga yang kini mulai tampak di ufuk: AI fisik. Di sinilah Huang mengajukan ajakan yang barangkali terdengar tak lazim bagi sebagian orang. Bahwa masa depan bukan hanya soal komputer yang bisa menulis atau menggambar, melainkan soal mesin yang bisa bergerak, membaca tekanan tanah, memahami arah angin, merespons sentuhan, dan bertindak dalam dunia nyata. Dunia yang memiliki gaya gravitasi, kelembapan, suhu, dan hukum-hukum lain yang tak tertulis dalam kode.
Untuk menjawab tantangan itu, kata Huang, bukan ilmu komputer yang akan menjadi kunci utama. Melainkan fisika—ilmu yang diam-diam selalu menyertai kehidupan. Ilmu yang memberi kerangka untuk memahami bagaimana benda jatuh, mengapa suara merambat, atau bagaimana cahaya membelok. Jika suatu hari anak-anak kita merancang robot yang mampu berjalan di jalan becek, atau lengan mekanik yang bisa merasakan kekasaran permukaan benda, mereka tak akan cukup hanya dengan belajar algoritma. Mereka harus mengerti hukum gerak, torsi, elastisitas, tekanan, dan semua hal yang diajarkan oleh fisika.
Huang tidak sedang memuliakan fisika semata sebagai ilmu. Ia ingin mengajak kita menengok kembali struktur pengetahuan yang selama ini kita anggap praktis. Dalam dunia di mana coding bisa didelegasikan kepada mesin, maka ilmu dasar seperti fisika, matematika, dan logika justru menjadi jangkar berpikir yang tak tergantikan. Bukan karena ia kuno, melainkan karena ia menyentuh dasar kenyataan yang tak bisa dipalsukan.
Namun tentu saja, ajakan ini tidak bisa dipahami secara mutlak. Sebab bagaimanapun juga, teknologi tetap membutuhkan pengembang yang memahami sistem. Pengelolaan data, rancangan arsitektur komputasi, keamanan siber, dan pengembangan platform digital masih sangat bertumpu pada keahlian ilmu komputer. AI tidak lahir begitu saja; ia dilatih, dioptimalkan, dan dirawat. Dan itu semua tetap menuntut orang-orang yang mengerti bahasa mesin dan cara berpikir algoritmik.
Karena itu, ajakan Huang bukan sebuah vonis atas redupnya ilmu komputer, melainkan semacam pengingat. Bahwa arah masa depan teknologi tidak akan hanya berkutat pada dunia layar, tetapi akan menyentuh bumi, air, dan udara. Dalam dunia seperti itu, pemahaman fisika menjadi syarat agar teknologi mampu hidup bersama kenyataan.
Ada pula kepentingan strategis yang tidak bisa diabaikan. Nvidia, sebagai perusahaan yang kini mengembangkan platform simulasi fisika bernama Omniverse, tentu memiliki kepentingan terhadap meningkatnya kebutuhan pemodelan dunia nyata. Dalam pengertian ini, seruan Huang agar anak muda belajar fisika juga merupakan cerminan dari visi korporasi: menciptakan ruang virtual yang bisa mereplikasi dunia fisik secara akurat. Namun di balik itu, tetap ada gagasan yang jernih: bahwa manusia tidak bisa selamanya tinggal di dunia abstrak. Kita akan selalu kembali pada tanah tempat kaki berpijak.
Dalam gelombang ketiga yang kini mulai terbentuk, mereka yang memiliki pemahaman tentang gerak, massa, gaya, dan waktu akan lebih siap merancang teknologi yang bisa bersentuhan dengan dunia. Fisika, dalam pemahaman ini, bukan sekadar mata kuliah wajib yang terlupakan begitu wisuda selesai. Ia bisa menjadi bahasa masa depan.
Anak-anak yang hari ini belajar tentang gaya gesek dan medan magnet mungkin akan menjadi perancang kendaraan otonom yang lebih aman. Mereka yang memahami resonansi dan hukum Newton mungkin akan membantu robot menjelajahi medan rawan bencana. Mereka yang belajar fisika partikel mungkin kelak menemukan material baru untuk baterai ramah lingkungan.
Dan barangkali, pelajaran terpenting dari semua ini adalah bahwa masa depan tidak bisa dibaca hanya dari tren, tetapi juga dari kedalaman. Dalam dunia yang makin canggih, yang justru dibutuhkan adalah mereka yang tetap mampu berpikir mendasar. Fisika tidak menjanjikan jawaban yang cepat, tetapi mengajarkan cara melihat dunia secara jernih. Mungkin itu bekal yang paling berharga di zaman ketika segalanya bisa diciptakan, kecuali kesadaran untuk mengerti.