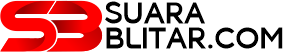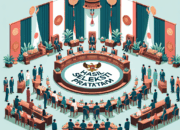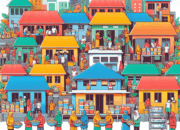Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar mengeluarkan pernyataan resmi yang menguatkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 dari MUI Provinsi Jawa Timur tentang penggunaan sound horeg—istilah populer untuk sistem pengeras suara bertenaga tinggi yang kerap digunakan dalam hajatan hingga pertunjukan jalanan. Melalui unggahan digital di akun Instagram @muikotablitar, fatwa ini dikemas sebagai panduan moral dan sosial dalam menyikapi gejala kebisingan yang kian mengakar dalam praktik budaya lokal.
Dalam dokumen yang berjudul Fatwa Tentang Penggunaan Sound Horeg, terdapat enam poin utama yang mengatur batas etika, hukum, dan akhlak dalam pemanfaatan teknologi audio di ruang publik.
Pertama, MUI menyatakan bahwa penggunaan teknologi audio digital adalah bagian dari kemajuan yang patut disyukuri, selama tidak bertentangan dengan hukum positif negara maupun prinsip-prinsip syariat Islam.
Kedua, ditegaskan pula bahwa hak setiap warga untuk berekspresi dijamin, asalkan tidak melanggar hak asasi pihak lain, terutama hak atas ketenangan dan kesehatan lingkungan.
Namun pada poin ketiga, MUI mulai menegaskan larangan yang lebih substansial. Penggunaan sound horeg dengan volume melebihi batas wajar yang membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, atau bahkan menyajikan konten bermuatan maksiat seperti musik yang disertai joget dengan pakaian terbuka, dikategorikan haram secara mutlak. Baik dilakukan di tempat umum, gang kampung, maupun saat berkeliling membawa kendaraan bermusik keliling (yang marak di perkampungan), semua bentuknya masuk dalam kategori yang dilarang.
“Tidak ada toleransi jika sound digunakan untuk menyebar kemunkaran dan kerusakan sosial,” tegas MUI dalam redaksi tertulis.
Fatwa ini juga membedakan antara penggunaan yang merusak dan yang bersifat maslahat. Pada poin keempat, MUI memperbolehkan penggunaan sound system selama dalam batas wajar dan digunakan untuk kegiatan positif seperti pengajian, pernikahan, hingga shalawatan. Artinya, bukan teknologinya yang dilarang, tetapi cara dan niat pemanfaatannya.
Hal yang tak kalah penting muncul di poin kelima. MUI menyoroti fenomena battle sound, yakni lomba keras-kerasan speaker antar komunitas yang menjamur di sejumlah wilayah. Aktivitas ini disebut menimbulkan mudarat dan dianggap sebagai bentuk pemborosan harta (tabdzir) yang dihukumi haram. Kebiasaan ini bahkan seringkali menggunakan dana kolektif kampung, yang kemudian digunakan untuk ‘pamer kekuatan suara’, bukan untuk kegiatan produktif.
Di bagian akhir, fatwa menyatakan bahwa siapa pun yang menimbulkan kerugian akibat kebisingan berlebihan—baik berupa gangguan kesehatan, retaknya kaca rumah warga, atau gangguan tidur anak-anak—maka wajib memberikan ganti rugi. Ini mempertegas posisi hukum syariat yang berpihak pada prinsip tanggung jawab dan keadilan sosial.
Di lapangan, suara masyarakat terkait fatwa ini terbagi dua. Warga seperti Sulastri, ibu rumah tangga di Kelurahan Karangsari, merasa lega. “Setiap malam ada yang muter remix sampai jam dua. Anak saya enggak bisa tidur. Semoga fatwa ini benar-benar ditegakkan,” katanya.
Namun dari sisi penyedia jasa sound, fatwa ini dianggap menekan ruang usaha. Wahyu, salah satu pemilik rental sound system di Blitar Selatan, mengaku bingung menentukan batasan “berlebihan”. “Kalau standarnya pakai rasa telinga orang, itu bisa beda-beda. Yang jelas, saya usahakan tetap sesuai waktu dan volume,” ujarnya.
Pengamat budaya lokal, Imam Sudharsono, menyebut fatwa ini sebagai langkah awal mengembalikan ruang sosial ke rel keseimbangan. “Sound horeg itu semacam ‘terompet eksistensi’ warga kelas bawah. Kadang bukan sekadar hiburan, tapi pernyataan bahwa mereka ada. Maka pelarangan perlu diimbangi ruang ekspresi alternatif,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkot Blitar menyatakan siap mendukung sosialisasi fatwa ini dan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam merayakan momentum kebudayaan tanpa melanggar etika sosial.
Fatwa ini bukan instrumen hukum positif, tapi ia adalah cermin moral. Dan moral publik, jika dibiarkan dikeraskan tanpa kendali, kadang berubah menjadi gaduh yang menindas. Kini, pertanyaannya bukan hanya soal seberapa keras suara yang keluar dari speaker, tetapi seberapa besar kesadaran yang keluar dari hati mereka yang menyalakannya.