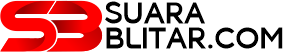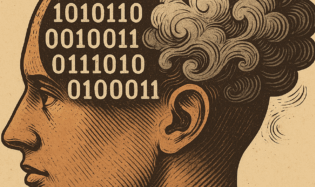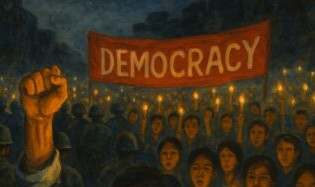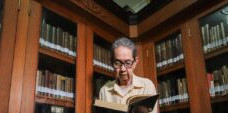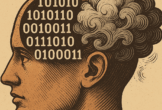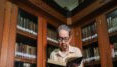Ada masa ketika politik tidak lagi tampil sebagai arena diskusi, melainkan sebagai panggung komedi gelap yang memaksa kita tertawa pahit. Panggung itu bernama Gedung DPR, rumah rakyat yang lebih sering terasa seperti klub eksklusif dengan tiket masuk seharga miliaran rupiah. Dan pada Agustus 2025, pentasnya mencapai klimaks yang tidak akan mudah dilupakan: rakyat berkerumun di luar, sementara di dalam gedung diumumkan bahwa para legislator akan menerima tunjangan perumahan lima puluh juta rupiah per bulan. Angka itu tidak hanya menghina logika, tetapi juga melecehkan nurani kolektif.
Bagaimana tidak? Di kota yang sama, guru honorer masih bertahan hidup dengan satu sampai dua juta rupiah per bulan. Seorang buruh pabrik hanya membawa pulang lima juta lebih sedikit dari satu tunjangan DPR. Lalu dengan wajah tanpa rasa bersalah, wakil rakyat berdalih rumah dinas lama tidak layak, seakan-akan Jakarta kehabisan kontrakan dan apartemen. Ironi makin menusuk ketika seorang legislator—Ahmad Sahroni—dengan enteng menyebut siapa pun yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tertolol sedunia”. Pernyataan itu bukan sekadar blunder, melainkan testimoni publik bahwa jarak antara rakyat dan wakilnya sudah mencapai titik yang tak lagi bisa dijembatani.
Namun tunjangan lima puluh juta hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada daftar panjang fasilitas lain: dana riset yang jarang digunakan untuk riset, uang reses yang lebih mirip ongkos tur politik, tunjangan komunikasi, hingga mobil dinas yang tak pernah macet di jalanan yang sama dengan rakyat. Saat negara memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan dengan alasan efisiensi, parlemen justru menambahkan barisan privilese. Slogan “efisiensi” ternyata hanya berlaku untuk mereka yang tak berkuasa.
Rakyat bukan hanya marah karena angka itu besar, tetapi karena angka itu keluar di saat dompet mereka makin tipis. Pajak terus naik, beban distribusi makin berat, sementara kualitas pelayanan publik makin menurun. Rasio pajak di semester pertama 2025 bahkan merosot ke 8,4%, tetapi bukan karena rakyat mendapat keringanan, melainkan karena tata kelola amburadul. Pemerintah lalu menambal kekurangan dengan memaksa daerah menaikkan pajak lokal, membuat pasar basah, warung kecil, dan pengemudi ojek online ikut menanggung beban. Di saat bersamaan, subsidi gas LPG 3 kilogram dikurangi, distribusinya dipersempit, dan masyarakat miskin harus antre berjam-jam untuk sekadar bisa memasak nasi. Hidup sehari-hari menjadi antrian panjang, sementara di Senayan hidup adalah rapat yang diakhiri makan siang mewah.
Kemarahan yang tadinya berserakan akhirnya menemukan simbol. Tunjangan DPR adalah cermin yang memperlihatkan betapa dalamnya jurang ketidakadilan. Dan rakyat pun turun ke jalan: buruh dengan tuntutan Hostum, mahasiswa dengan pekikan anti-dinasti, petani, pelajar, hingga ojek online dengan jaket hijau yang hari itu tak lagi mengantar makanan, melainkan membawa tuntutan. Mereka datang bukan hanya membawa spanduk, tetapi juga bahasa baru perlawanan. Bendera bajak laut One Piece berkibar sebagai simbol kebebasan tanpa ideologi kaku. Tagar #IndonesiaGelap viral sebagai satire terhadap janji “Indonesia Terang”. Meme, plesetan, emoji tawa—semua menjadi senjata melawan narasi kekuasaan.
Namun seperti biasa, ketika suara rakyat membesar, negara merapatkan barikade. Polisi menjanjikan pendekatan humanis, tanpa senjata api, penuh persuasif. Tapi sejarah politik Indonesia selalu lebih jujur daripada janji pejabatnya. Pada 25 Agustus, gas air mata sudah menyelimuti Slipi dan Semanggi. Dua hari kemudian, pada 28 Agustus, puluhan ribu buruh mengepung DPR, pagar barikade diterobos, dan aparat menjawab dengan water cannon. Malam harinya, tragedi lahir: seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terlindas mobil rantis Brimob.
Afan bukan pahlawan. Ia tidak naik panggung, tidak berorasi, tidak menulis manifesto. Ia hanya rakyat biasa yang tubuhnya kebetulan berada di jalur represif. Namun justru karena itulah ia menjadi simbol. Simbol bahwa yang paling pertama terlindas bukanlah elite, bukan aktivis dengan mikrofon, melainkan rakyat kecil yang hanya ingin hidup layak. Afan bukan martir pilihan, ia martir keterpaksaan. Tubuhnya yang remuk di aspal adalah metafora paling telanjang dari keadaan kita: rakyat dilindas, lalu diminta sabar, sementara elite duduk nyaman dengan tunjangan barunya.
Sejarah mencatat banyak nama besar dalam perlawanan: mahasiswa Trisakti 1998, korban Malari 1974, aktivis Tritura 1966. Tetapi Afan berbeda. Ia tidak datang dari ruang ideologi, melainkan dari aplikasi ponsel tempat ia mencari nafkah harian. Justru karena itu, kematiannya terasa lebih menusuk. Ia adalah kita: yang tidak pernah diundang ke meja perundingan, tapi selalu membayar harga paling mahal dari kebijakan yang dibuat di meja itu.
Setelah tragedi, Kapolri dan Kapolda meminta maaf, biaya pemakaman ditanggung negara, penyelidikan dijanjikan. Ritual itu selalu sama, hanya nama korbannya yang berganti. Dari mahasiswa, buruh, petani, hingga kali ini seorang pengemudi ojek online. Negara tampak seperti aktor yang lupa bahwa setiap permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah bagian dari skenario lama.
Lebih pahit lagi, banyak dari mereka yang dulu berteriak reformasi kini duduk di kursi yang sama dengan mereka yang dulu mereka kritik. Aktivis 1998 yang pernah diusir aparat kini menjadi bagian dari aparat politik. Idealismenya melebur dalam anggaran, dalam rapat, dalam tunjangan. Seakan kursi itu punya kekuatan gaib: siapa pun yang mendudukinya akan lupa pernah berdiri di jalan.
Maka epilog ini seharusnya membuat kita bertanya: berapa kali lagi sejarah harus berulang? Berapa Afan lagi yang harus mati agar elite mengerti bahwa demokrasi bukan sandiwara? Apakah rakyat harus terus dianggap “tertodoh” hanya karena berani marah pada ketidakadilan?
Afan Kurniawan mungkin tidak akan tercatat dalam buku pelajaran sejarah, tapi namanya adalah catatan kaki yang lebih jujur daripada pidato kenegaraan mana pun. Ia bukan pahlawan dengan patung megah, melainkan simbol dari penindasan sistematis yang dialami jutaan orang setiap hari. Ia adalah tubuh yang tidak sempat diselamatkan, tapi justru karena itu ia menjadi penanda: bahwa demokrasi kita masih terancam bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh kesombongan dari dalam.
Selama tunjangan lebih mahal daripada empati, tragedi semacam ini akan terus lahir. Dan kita, rakyat yang disebut tolol, mungkin hanya punya satu kekuatan: mengingat. Mengingat Afan, mengingat setiap luka, mengingat bahwa kursi-kursi itu hanyalah pinjaman dari suara yang terlindas.