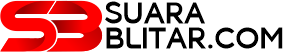Perang Jawa dan Dampak Eksploitasi Kolonial Terhadap Rakyat
Sistem perpajakan yang menekan dan praktik korupsi yang merajalela menjadi latar belakang munculnya Perang Jawa (1825-1830), yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dalam sketsa Perang Jawa 1825, Raden Adipati Ario Joyodiningrat menggambarkan berbagai jenis pajak yang mengikat masyarakat, seperti pacumpleng (pajak pintu), grigajih (pajak orang), hingga pajak sawah dan kuda. Pajak-pajak ini tidak hanya menyengsarakan secara ekonomi, namun juga merendahkan martabat rakyat Jawa.
Praktik korupsi dalam sistem pemerintahan juga turut menyumbang masalah ini. Joyodiningrat mencatat bahwa tanah bengkok yang dimiliki oleh pejabat, seperti bupati dan pangeran, ditahan pasca kematian mereka, dengan pendapatannya justru mengalir ke kantong pribadi Patih Danurejo IV. Hal ini menciptakan dampak yang merugikan masyarakat, di mana jabatan pemerintahan dijadikan komoditas, dan pejabat desa yang tidak mampu membayar pajak diancam dipecat.
Kondisi ini berimbas langsung pada birokrasi desa, sehingga mengganggu stabilitas dan memicu konflik di antara masyarakat. Joyodiningrat menekankan, “Jika bekel tidak mau membayar pajak tanah, posisinya akan digantikan oleh orang yang mampu membayar.” Lingkungan keraton sebagai pusat kekuasaan juga tak luput dari degradasi moral. Irfan Afifi menyebutkan bahwa banyak pangeran yang terjerumus dalam kebudayaan Barat dan praktik korupsi.
Strategi kolonial yang sistematis memperparah degradasi ini. Dengan melemahkan elite tradisional, para penjajah berhasil membentuk lingkaran setan antara elit dan rakyat. Pangeran Diponegoro, yang merasakan dampak dari kebijakan yang merugikan, kemudian mengambil langkah signifikan. Pada pertengahan 1825, ketika lahan miliknya di Tegalrejo tiba-tiba dipasang patok tanpa pemberitahuan oleh Patih Danurejo IV, Diponegoro menolak dan meminta pemecatan Patih tersebut. Namun, permintaannya ditolak oleh Residen Jogjakarta, A.H. Smissaert.
Merasa tak ada jalan lain, Diponegoro kemudian beruzlah untuk meminta bimbingan spiritual. Keputusan untuk mengangkat senjata melawan ketidakadilan diambil, dan ia mendapat dukungan luas dari masyarakat. Perang Jawa kemudian menjadi gerakan populer yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pangeran Diponegoro menerapkan struktur militer yang terinspirasi dari Angkatan Bersenjata Turki Utsmani, memberdayakan pasukannya dengan nama-nama yang khas.
Sejarah mencatat, perang tersebut menimbulkan korban jiwa yang besar, dengan sekitar 200.000 nyawa rakyat Jawa melayang, ditambah dengan 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang berperang di pihak Belanda. Kerugian finansial bagi Belanda pun mencapai 20 juta Gulden.
Perang ini akhirnya berakhir secara curang pada tahun 1830, saat Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 8 Januari 1855, dalam usia 69 tahun. Perang Jawa menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan eksploitasi yang menyengsarakan rakyat, serta menyisakan jejak sejarah yang tak terlupakan di tanah air.