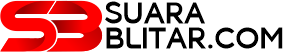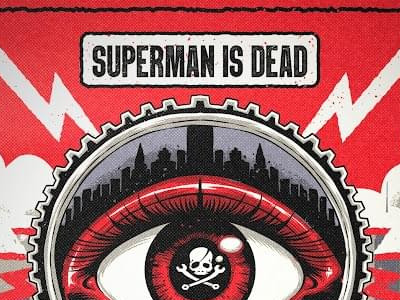Dalam arus zaman yang makin kabur batas antara kenyataan dan manipulasi, lagu “1984” dari Superman Is Dead (SID) dan Keroncong Seba hadir seperti suara yang menolak jinak. Ia bukan sekadar bunyi-bunyian—ia adalah peringatan, panggilan, sekaligus cermin yang memantulkan wajah buram demokrasi, kebebasan, dan disinformasi yang kian mengakar. Dalam tiga menit yang penuh distorsi, punk, dan gesekan senar tradisi, lagu ini menawarkan sesuatu yang jarang kita temui dalam musik populer Indonesia: keberanian menyentuh pusat saraf kekuasaan.
“1984” tidak membungkus protesnya dengan estetika yang manis. Lagu ini tidak lahir dari ruang produksi yang steril, tapi dari perut zaman yang gerah—ketika bencana dijadikan panggung politik, ketika media menjadi alat penyulap kenyataan, dan ketika masyarakat diminta tersenyum dalam diam, di bawah bayang-bayang krisis yang tak pernah selesai. Kalimat seperti “tekanlah populasi, santun lenyapkan senyum” bukanlah metafora yang dibumbui puisi. Ia adalah hasil pengamatan sosial yang tak disensor, suara jujur dari bawah.
Mengacu langsung pada novel 1984 karya George Orwell, lagu ini menyerap semangat perlawanan terhadap pengendalian total informasi. Dalam narasi Orwell, Big Brother mengawasi segalanya. Dalam versi SID dan Keroncong Seba, yang diawasi bukan hanya tubuh, tapi pikiran. Yang dibungkam bukan hanya suara, tapi nalar. Kekuasaan tidak lagi tampil brutal, melainkan membaur dalam birokrasi, dalam berita pagi, dalam himbauan resmi yang terdengar logis namun menyesatkan. Dan semua ini terjadi bukan di masa depan. Ia sudah di sini. Ia sudah terjadi.
Kehadiran Keroncong Seba di lagu ini menambah lapisan makna yang tidak bisa diremehkan. Musik keroncong, yang selama ini diasosiasikan dengan masa lalu, justru dihidupkan kembali dalam konteks perlawanan. Seolah-olah SID sedang mengatakan: sejarah bukan museum, dan tradisi bukan warisan mati. Ketika punk dan keroncong bertemu, yang lahir adalah bentuk seni baru yang bukan hanya menolak tunduk, tapi juga menolak dilupakan. Bunyi-bunyi lama ini tidak datang membawa nostalgia, melainkan ingatan: bahwa bangsa ini pernah punya suara yang keras, jernih, dan tidak takut.
Lagu ini tidak berbicara tentang satu isu. Ia menyentuh banyak hal dalam sekali tarikan napas: wabah, bencana ekologis, polarisasi politik, kebebasan sipil yang dikekang oleh alasan keamanan, dan literasi publik yang dipelintir oleh algoritma. Dalam kondisi seperti itu, 1984 menjadi seperti manifesto kecil yang dikirim diam-diam dari dunia bawah tanah. Ia tidak memohon untuk didengar. Ia hanya menyatakan diri, dan dari sanalah justru kekuatannya muncul.
Bobby Kool dan Eka Rock tidak mencoba menyembunyikan kemarahan mereka. Namun yang mereka tampilkan bukan emosi kosong. Ada kedalaman dalam setiap frasa. Ada logika di balik setiap repetisi. Dan yang lebih penting: ada ajakan untuk berpikir, bukan hanya marah. Lagu ini tidak berhenti di gugatan. Ia juga mengusulkan jalan: literasi, logika, dan keberanian berpikir kritis. Ia menantang pendengar bukan untuk ikut arus, tapi untuk bertanya: siapa yang mengendalikan narasi yang kita telan tiap hari?
Dalam konteks Indonesia hari ini—di mana debat publik mudah tergelincir ke polarisasi biner, di mana kritik dianggap pengkhianatan, dan di mana suara-suara alternatif sering dikerdilkan—lagu seperti ini memiliki fungsi yang nyaris langka. Ia menjadi ruang di mana perlawanan tetap bisa diungkapkan secara artistik, tanpa kehilangan tajinya. Lagu ini bukan agitasi murahan. Ia adalah kritik yang dibangun dengan kesadaran politik, sejarah, dan estetika sekaligus.
Penerbitan lagu ini pada September 2024 bukan tanpa makna. Ia lahir di tengah ketegangan global dan domestik: pandemi yang masih menyisakan trauma, krisis iklim yang tak ditangani dengan serius, serta atmosfer politik yang makin penuh kepura-puraan. Dalam situasi seperti itu, lagu 1984 bukan hanya penting—ia perlu.
Kehadiran musik seperti ini seharusnya menjadi pengingat: bahwa seni bukan sekadar hiburan. Dalam bentuknya yang paling jujur, seni adalah bentuk pengetahuan, adalah sikap. SID dan Keroncong Seba tidak sedang tampil eksperimental. Mereka sedang memperluas medan kritik. Mereka mengembalikan seni ke fungsinya yang asli—membantu manusia memahami dunia, dan bila perlu, menggugatnya.
Lagu ini tidak menjanjikan solusi. Ia bukan manifesto politik. Tapi justru karena itu, ia bekerja lebih dalam. Ia tidak memberi arah, tapi memberi cermin. Dan dalam dunia yang sibuk membagikan “apa yang harus dilakukan”, terkadang kita butuh sesuatu yang lebih sunyi tapi jernih: sesuatu yang hanya meminta kita membuka mata.
1984 adalah lagu yang mungkin tidak akan diputar di radio pagi. Ia tidak menawarkan pelipur lara. Tapi justru karena itu, ia akan dikenang. Dalam sejarah musik Indonesia, lagu ini akan berdiri di satu garis yang jarang dilalui: jalur yang menolak jinak, menolak didiamkan, dan menolak dijinakkan oleh pasar atau penguasa.
Dan pada akhirnya, lagu ini seperti bisikan yang ditulis di dinding: kamu boleh tidak setuju, kamu boleh menertawakannya, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Karena sekali kamu mendengarnya, dunia tak lagi terdengar sama.
https://music.youtube.com/watch?v=Jiyae00CIaI&si=tYUzMTp2sQv_FU7R