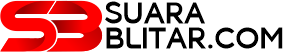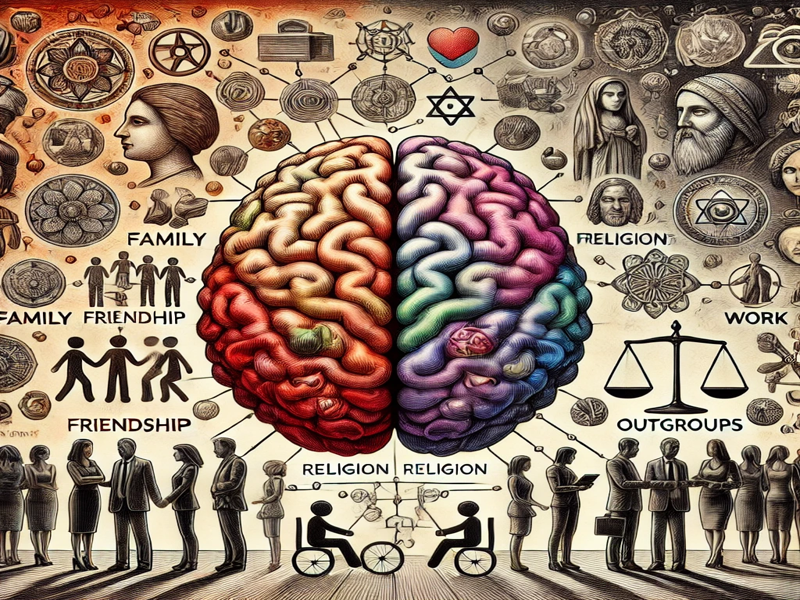Dalam keseharian, kita cenderung menerima begitu saja kenyataan yang tampak di depan mata. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan di balik kebiasaan itu: otak manusia membiarkan kita “buta” selama kurang lebih dua jam setiap harinya. Fakta ini menantang pemahaman kita tentang kesadaran dan persepsi. Memahami mekanisme tersebut bukan hanya soal membedah kerja otak, tapi juga tentang mengenali cara kita mengalami dunia.
Penglihatan menjadi indra utama dalam memberi informasi tentang lingkungan sekitar. Tapi secara teknis, kita hanya melihat dalam resolusi tinggi pada area seukuran kuku jempol tangan. Sisanya, kabur. Dalam tiap detik, mata bergerak cepat tiga hingga empat kali, dalam gerakan kecil yang disebut saccade. Selama gerakan ini—yang berlangsung sekitar 50 milidetik—otak mematikan input visual agar kita tak menangkap efek blur dari pergerakan mata. Agar pengalaman visual terasa utuh, otak mengisi celah-celah kosong itu dengan perkiraan. Jika diakumulasi dalam sehari, jumlah waktu saat kita sebenarnya tidak melihat secara aktif bisa mencapai dua jam.
Tapi tak hanya penglihatan yang diedit. Persepsi waktu pun ikut disusun ulang. Ketika seseorang mengaduk kopi, cahaya dari permukaan cairan mencapai mata dalam waktu sekitar 1,3 nanodetik. Suara gesekan sendok dan cangkir tiba di telinga dalam waktu sekitar 1,2 milidetik. Sensasi panas di jari muncul dalam 50 milidetik. Meski semua itu terjadi dalam urutan berbeda, kita merasakannya sebagai satu momen utuh. Ini karena otak menunggu sejenak—sekitar 0,3 hingga 0,5 detik—untuk menggabungkan semua input sensorik dan menyusunnya menjadi satu cerita yang bisa dicerna.
Dengan kata lain, apa yang kita sebut “saat ini” sebenarnya adalah gabungan dari kejadian yang sudah lewat dan perkiraan tentang apa yang sedang berlangsung. Bahkan dalam aktivitas biasa seperti menonton pertandingan tenis meja, otak kita tidak menerima informasi secara instan. Ia mesti memprediksi posisi bola berdasarkan data yang sudah usang, sebab dibutuhkan waktu untuk cahaya masuk ke mata, diterjemahkan, lalu disadari.
Dalam olahraga cepat seperti itu, otak bekerja dalam mode antisipatif. Ia menebak ke mana arah bola, bukan berdasarkan penglihatan terkini, tapi dari pola-pola sebelumnya. Bahkan sebelum Anda sadar bahwa Anda akan bergerak, otak sudah mengirim sinyal ke otot. Respons yang cepat itu tidak selalu melewati jalur kesadaran. Dalam konteks ini, banyak keputusan terjadi bukan karena kehendak sadar, tapi karena sistem saraf sudah lebih dulu mengambil alih.
Hal yang sama terjadi saat kita berjalan. Meski terasa seperti kita mengendalikan langkah sendiri, sesungguhnya otak bekerja dalam tiga garis waktu sekaligus: memproses masukan sensorik dari langkah sebelumnya, menilai kondisi tubuh saat ini, lalu memperkirakan gerakan selanjutnya. Sebelum kaki menyentuh tanah, otak sudah merancang gerak kaki berikutnya. Jika tiba-tiba muncul kulit pisang di jalur kita, pusat refleks di batang otak dan sumsum tulang belakang sudah bersiap menyelamatkan keseimbangan, bahkan sebelum kita sadar ada bahaya.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam: apakah kita ini hanya hasil dari prediksi otak? Rasa lapar, letih, bahkan emosi bukan hanya reaksi, melainkan bentuk antisipasi. Jika seseorang terbiasa makan siang pukul 12, maka sebelum jam itu tiba, tubuh sudah memproduksi hormon lapar. Bukan karena kebutuhan fisik yang mendesak, tapi karena sistem di otak telah memprediksi dan bersiap.
Emosi pun serupa. Jika Anda sering merasa cemas sebelum menghadiri acara sosial, otak akan menyiapkan tubuh untuk merasakan cemas itu bahkan sebelum kejadian dimulai. Mekanisme ini bekerja seperti skrip yang sudah ditulis sebelumnya. Kita merasa sedang merespons dunia luar, padahal banyak dari apa yang kita alami adalah hasil susunan dan proyeksi dalam kepala.
Meski begitu, kita bukan hanya penonton pasif dari pertunjukan saraf. Di balik sistem prediktif yang kompleks itu, kita memiliki ruang untuk menyusun ulang cerita. Kesadaran memberi kita kemampuan merencanakan, merenung, dan mengambil jarak dari narasi otomatis yang dibentuk otak. Kita bisa mengingat dengan cara yang berbeda, menafsirkan ulang kejadian, dan memilih sikap yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pola lama.
Maka, yang kita sebut kenyataan sehari-hari sesungguhnya adalah peta yang disusun dari berbagai asumsi, tebakan, dan konstruksi saraf. Kita hidup dalam hasil editan otak, sebuah film yang terus disunting agar berjalan lancar. Bukan berarti kita terputus dari dunia nyata, melainkan bahwa pengalaman kita terhadap dunia itu adalah hasil kerja keras sistem yang terus-menerus memperkirakan, menambal, dan mengoreksi.
Kesadaran akan hal ini bisa menjadi semacam pembuka jendela. Ia tidak sekadar menjelaskan bagaimana kita memproses dunia, tetapi juga menawarkan ruang untuk menjelajah cara baru dalam melihat, merasa, dan memilih. Karena meski otak memimpin banyak proses, arah langkah tetap bisa kita tentukan.