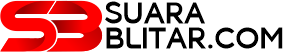Dalam beberapa tahun terakhir, bersih desa mengalami transformasi yang tak sepenuhnya disadari banyak orang: dari laku spiritual menjadi pesta decibel. Di banyak desa, terutama di kawasan yang tersambung dengan akses internet dan pengaruh urban, bersih desa bukan lagi semata-mata ritual keselarasan kosmik—ia juga telah menjelma menjadi panggung bagi sound horeg, panggung joget, lampu strobo, MC yang berceloteh seperti kanal YouTube, dan barisan knalpot brong yang ikut konvoi layaknya pengawal gaib yang kehilangan kitab suci.
Ini bukan kebetulan. Dalam dunia yang menggantungkan eksistensinya pada visibilitas—dilihat, didengar, direkam, dan disiarkan—ritual-ritual lama pun harus bersaing dengan algoritma. Sound system menjadi semacam totem baru. Ia bukan sekadar pengeras suara, tetapi simbol kemeriahan, afirmasi status sosial, dan saluran eksistensi. Sebuah desa dianggap rame dan sukses menyelenggarakan bersih desa jika desibel menggetarkan genteng dan unggahan TikTok-nya mendapat ribuan likes. Barangkali ini bentuk baru dari “sedekah digital”—mengunduh video sesajen dan joget sebagai persembahan kepada para dewa bernama followers.
Namun ada yang bergeser secara mendalam. Tradisi yang awalnya bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam kini justru menciptakan polusi bunyi, sampah plastik dari bungkus nasi kotak, dan terkadang ketegangan sosial akibat pesta malam yang berujung keributan. Beberapa warga yang dulu ikut nyadran kini memilih menutup jendela rapat-rapat saat malam pesta tiba. Mereka tidak menemukan pantulan nilai yang sama antara doa-doa leluhur dan suara dentum DJ remix lagu koplo yang dimainkan hingga dini hari.
Di titik ini, sound horeg dalam bersih desa menjadi semacam ironi antropologis. Ia adalah bentuk modern dari “ritual perayaan”, namun kehilangan struktur kosmik yang melandasinya. Bila dalam upacara tradisional ada waktu untuk hening dan waktu untuk gegap gempita, kini semuanya dilebur dalam satu frekuensi: keras. Sangat keras. Sampai-sampai suara jangkrik pun menyerah.
Fenomena ini menyiratkan transisi peradaban dari spiritualitas agraris menuju estetika sensorik. Yang dulunya memuja harmoni dengan kekuatan tak kasat mata, kini memuja keterlihatan dan keterdengaran. Tidak cukup membuat selamatan kecil di pinggir sawah, harus ada panggung, penyanyi tamu, dan baliho besar dengan nama-nama sponsor lokal. Bersih desa yang dulunya bersifat lintas dunia (manusia dan gaib) kini menjadi lintas platform—offline dan online, desa dan Jakarta, dukun dan YouTuber.
Namun, tidak semua layak dicela. Di balik dentuman itu, masih ada keinginan tulus untuk berkumpul. Ada kerinduan kolektif untuk memiliki satu momen dalam tahun yang memberi identitas. Bahkan ketika bentuknya berubah, fungsi sosialnya tetap: mengikat warga dalam semacam ritus, meski kini ritus itu berbentuk karaoke massal.
Pertanyaannya kemudian: apakah desa harus diam demi menghormati yang gaib, atau justru harus gaduh demi menunjukkan bahwa mereka masih hidup?
Barangkali jawabannya tidak pada diam atau gaduh, melainkan pada kepekaan. Jika sound horeg mampu diletakkan dalam kerangka yang peka terhadap ruang dan waktu—tidak mengusik lansia, tidak menghancurkan makna, tidak menggeser makna sedekah menjadi konsumsi tontonan—maka ia bisa menjadi bagian dari adaptasi budaya yang sah.
Namun jika ia dipaksakan menjadi pusat makna, maka bersih desa tak ubahnya menjadi pesta bunyi yang kehilangan akar. Suara tidak lagi digunakan untuk menyampaikan pesan kepada leluhur, melainkan untuk mengusir mereka pergi.
Dalam masyarakat yang kehilangan waktu hening, yang mengganti makna dengan hiburan, yang membiarkan malam desa kehilangan langit bintangnya karena sorotan panggung, bersih desa menjadi bukti bahwa tradisi bisa hidup—tapi tidak selalu utuh.
Dan mungkin inilah ironi terbesar dari sound horeg dalam bersih desa: ia memang menghidupkan malam, tapi tidak selalu membangunkan jiwa.