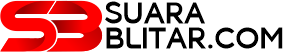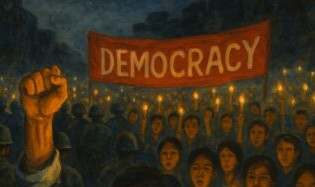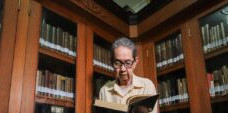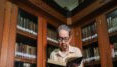Pajak, dalam sejarah, selalu menjadi medan ujian antara kekuasaan dan rakyat. Ia lahir dari ide yang terdengar polos: sebagian hasil kerja diserahkan kepada negara, lalu kembali dalam bentuk keamanan, jalan raya yang tidak berlubang, jembatan yang tidak ambruk sebelum upacara peresmian, sekolah yang benar-benar mengajar, rumah sakit yang tidak membuat pasiennya tambah sakit. Seperti semua kesepakatan yang bergantung pada niat baik, ia rapuh. Begitu niat itu hilang, pajak berubah wujud menjadi alat perampasan. Ia berhenti menjadi bahasa kemitraan dan menjelma sebagai bahasa perintah: dari atas, satu arah, tak butuh jawaban.
Kisahnya berulang di banyak tempat. Prancis akhir abad ke-18, misalnya, adalah drama besar tentang ketidakseimbangan. Versailles memancarkan cahaya lilin dari ribuan kristal, sementara di desa-desa roti menjadi barang mewah. Para bangsawan dan gereja bebas dari pajak, seakan hak istimewa mereka bukan sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Semua beban diarahkan kepada petani, buruh kota, dan pedagang kecil—orang-orang yang bekerja paling keras dan mendapat paling sedikit. Angka-angka pajak pada buku catatan bukan lagi sekadar hitungan. Ia menjelma menjadi rasa perih di punggung, lapar di perut, dan kemarahan yang menunggu kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, ia meledak menjadi Revolusi. Monarki patah, kepala raja dipisahkan dari tubuhnya, dan Prancis masuk ke musim panjang kekacauan. Pelajaran dari sini bukan tentang besar kecilnya pungutan, melainkan tentang rasa keadilan yang diinjak-injak. Sebab begitu rasa itu hancur, logam baja pun akan pecah.
Namun, jauh sebelum itu, Kekaisaran Romawi Barat sudah memberi contoh yang sama menyedihkan. Pajak di sana menjadi semacam peras darah tanpa batas. Kaisar-kaisar seperti Diocletian memungut pajak tinggi untuk membiayai perang, membangun benteng, dan menggemukkan birokrasi. Petani dipaksa menyerahkan hasil panen mereka, bukan sekadar karena negara butuh, tetapi karena aparatus pungut pajak haus. Dan haus yang satu ini tidak pernah reda. Korupsi menempel seperti jamur di dinding lembap: ia tumbuh bahkan tanpa cahaya. Lahan-lahan ditinggalkan, produksi pangan turun, perdagangan melemah. Ironisnya, tentara yang dibiayai dari pajak itu pada akhirnya tidak cukup kuat menahan invasi barbar. Roma runtuh bukan hanya karena pedang musuh, tetapi karena rongga di dalam tubuhnya sudah lama kosong.
Amerika di abad ke-18 punya cerita yang lebih singkat tapi sama tajamnya. Inggris, merasa sebagai induk yang berhak, memberlakukan pajak kepada koloninya tanpa memberi mereka hak untuk ikut memutuskan. “No taxation without representation” lahir bukan dari teori pajak di universitas, melainkan dari rasa jengkel yang terus dipupuk. Bagi para koloni, membayar pajak tanpa suara politik adalah tanda penaklukan, bukan kemitraan. Inggris meremehkan kemarahan ini, menganggapnya sekadar keluhan para pedagang dan pengacara. Tapi ternyata kemarahan itu menjalar ke petani, pelaut, hingga para penulis pamflet. Perang meletus, koloni merdeka, dan Inggris kehilangan permatanya. Di sini kita belajar bahwa pajak bukan hanya urusan fiskal, tapi soal harga dari kesetiaan.
Uni Soviet mengelolanya dengan cara yang lebih licin. Mereka tidak menyodorkan tagihan pajak seperti di negara kapitalis. Pajaknya tersembunyi, dibungkus dalam harga yang dikendalikan, kuota produksi, dan distribusi yang diatur ketat oleh negara. Dalam teori, semua demi pemerataan; dalam praktik, semua demi mempertahankan mesin birokrasi yang lamban dan korup. Tidak ada insentif untuk bekerja lebih baik, karena hasilnya akan sama saja. Rakyat membayar pajak dalam bentuk waktu yang hilang di antrian, tenaga yang terbuang untuk prosedur, dan peluang yang menguap begitu saja. Pada akhirnya, yang runtuh bukan hanya ekonomi, tapi juga keyakinan bahwa negara mampu mengatur hidup warganya.
Venezuela membawa kita ke bab modern dari kisah yang sama. Pajak tinggi, nasionalisasi yang mencekik, dan kebijakan moneter yang sembrono menciptakan hiperinflasi. Uang kehilangan nilainya secepat es meleleh di matahari Karibia. Orang-orang meninggalkan negara itu bukan hanya karena lapar, tetapi karena kehilangan keyakinan akan masa depan. Negara yang pernah kaya minyak ini menjadi ladang eksodus. Pajak, di sini, bukan lagi bahasa kerja sama, tetapi simbol dari sebuah sistem yang tak mampu membalas kepercayaan warganya.
Polanya jelas, hampir seperti rumus yang bisa dihafal: bebankan pajak hanya pada yang lemah, tarik tanpa memberi imbalan layanan publik, biarkan hasilnya menguap ke kantong pribadi—dan tunggulah ledakan. Ia mungkin datang sebagai revolusi, mungkin sebagai keruntuhan perlahan, atau sekadar perpindahan diam-diam orang-orang yang tak lagi percaya. Pajak, dalam bentuknya yang sehat, adalah tanda kemitraan: rakyat membayar karena percaya, negara menerima karena siap memberi. Ketika salah satu sisi hilang, hubungan itu runtuh. Runtuhnya tidak selalu dramatis; kadang ia seperti perahu bocor yang perlahan tenggelam tanpa ada teriakan.
Sejarah tidak pernah membenci pajak. Yang ia benci adalah pengkhianatan terhadap kontrak awalnya. Karena itu, setiap negara yang memandang pajak hanya sebagai cara untuk mengisi kas, tanpa memahami lapisan emosional dan moral di baliknya, sebenarnya sedang menulis undangan untuk krisisnya sendiri. Pajak bukan sekadar angka di laporan APBN, ia adalah cermin hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Dan seperti semua cermin, ia bisa memantulkan wajah kemakmuran bersama, atau menunjukkan retakan yang tak lagi bisa disembunyikan oleh cat atau retorika.
Yang ironis adalah, meskipun pola ini sudah terlihat begitu jelas di halaman sejarah, banyak negara—termasuk yang merasa dirinya modern—tetap mengulanginya. Mereka bersembunyi di balik istilah teknokratis: optimalisasi penerimaan, perluasan basis pajak, penyesuaian tarif. Kata-kata itu terdengar rapi, tapi sering kali menyamarkan satu fakta: beban yang sesungguhnya jatuh ke pundak yang paling rapuh. Dan dari situlah, lagi-lagi, cerita lama mulai ditulis ulang.