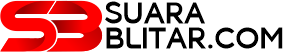Matraman, bagi banyak orang yang tak pernah benar-benar melewati wilayah ini, adalah sebatas peta di halaman belakang buku pelajaran sekolah atau nama samar dari wilayah yang serba ambigu. Ia tak semegah Surabaya, tak segegap-gempita Malang, apalagi sedinamis Yogyakarta. Ia berada dalam wilayah administratif Jawa Timur, namun secara kultural masih erat terhubung dengan sisa-sisa kultur Mataram kuno. Kota dan desa di kawasan ini, seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi, Madiun, Pacitan, dan Trenggalek, selalu hidup dalam dua kutub besar—di antara warisan Jawa yang kental dan ambisi pembangunan yang tak pernah benar-benar datang menyapa.
Selama bertahun-tahun, Matraman menjadi semacam zona abu-abu yang terpinggirkan dari arus utama pembangunan. Jika Anda melintasi jalur darat dari Surabaya ke Solo, Anda mungkin melewati Matraman tanpa sempat menyadari bahwa Anda sedang melewatinya. Wilayah ini tidak menawarkan lanskap modern yang mencolok, tidak pula menyajikan eksotisme turistik seperti di Banyuwangi atau Bromo. Ia hanya menyediakan wajah-wajah biasa yang tidak menuntut perhatian lebih: petani, pedagang kecil, pemuda pengangguran, atau pelajar yang berseragam seadanya.
Namun, setiap masyarakat yang terpinggirkan punya caranya sendiri untuk membuat suaranya didengar. Sejarah penuh dengan kisah tentang bagaimana warga kota kecil atau desa yang tidak dilirik oleh kekuasaan mencoba bersuara dengan caranya sendiri. Jika suara mereka tidak didengar lewat rapat desa atau musyawarah daerah, maka mereka akan mencari panggung lain—jalan raya, lapangan sepak bola desa, gang sempit, bahkan perempatan kecil di dekat pasar tradisional.
Di Matraman, panggung alternatif itu hadir dalam bentuk yang oleh banyak pihak disebut sebagai “gangguan ketertiban”: knalpot brong, pendekar jalanan, sound horeg, dan ledakan petasan yang terdengar sepanjang malam. Bunyi-bunyi ini mungkin bagi sebagian orang hanyalah ekspresi kenakalan, ketidakdisiplinan, atau bahkan kegagalan moral. Tetapi ketika kita melangkah lebih dekat, memeriksa di balik setiap deru mesin, sorak-sorai sound system, dan dentuman petasan, kita akan menemukan cerita tentang masyarakat yang suaranya terabaikan oleh pembangunan.
Pertama, mari bicara tentang knalpot brong. Knalpot dengan suara menggelegar bukanlah produk impor dari budaya asing. Ia lahir di bengkel-bengkel sederhana di pinggir jalan Matraman, hasil kreasi para pemuda yang punya banyak waktu luang, sedikit uang, dan nol peluang pekerjaan. Suara keras dari knalpot itu adalah cara mereka berteriak: “Kami ada, kami nyata!” Mereka mungkin tidak tahu bagaimana menyalurkan aspirasi lewat kanal-kanal politik resmi. Mereka mungkin tidak peduli siapa yang duduk di parlemen daerah atau siapa bupati yang baru saja terpilih. Tapi mereka tahu bagaimana membuat motor tua mereka bersuara, mencuri perhatian, dan mendapatkan pengakuan, meski sekadar tatapan jengkel dari pengendara lain.
Hal yang sama bisa ditemukan pada fenomena pendekar jalanan. Dalam benak kolektif masyarakat Jawa, pendekar identik dengan keberanian, harga diri, dan kekuatan yang berpijak pada tradisi lokal. Tapi di Matraman hari ini, pendekar bukan lagi sosok penjaga nilai tradisi yang luhur. Mereka adalah anak-anak muda yang belajar silat bukan demi pertarungan di gelanggang resmi, tapi sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap keterpinggiran mereka. Setiap gerakan mereka adalah cara untuk menegaskan identitas di tengah ketiadaan ruang ekspresi. Tubuh mereka bicara saat mulut mereka dianggap tidak penting.
Sound horeg bahkan punya narasi yang lebih kuat. Musik dangdut koplo, remix DJ, lagu-lagu campursari, atau bahkan sholawat yang diaransemen ulang dengan tempo tinggi diputar nyaring hingga subuh. Ini bukan sekadar hobi, melainkan ritual sosial yang membantu mereka bertahan di tengah kehidupan yang monoton dan minim harapan. Dalam volume tinggi itu, ada semacam ekstase kolektif yang membantu mereka melupakan, sejenak saja, betapa jauhnya jarak mereka dari pusat-pusat kemakmuran dan kekuasaan.
Namun, pertanyaan besar yang perlu diajukan adalah: mengapa suara-suara alternatif ini begitu marak di Matraman, tetapi tidak di tempat-tempat lain yang relatif lebih makmur dan terfasilitasi? Jawabannya terletak pada konsep dasar pembangunan yang selama ini dianut negara. Konsep pembangunan kita selama ini adalah top-down, birokratis, dan berorientasi kota. Ia bersifat teknokratis—didorong oleh indikator-indikator statistik seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah jalan raya yang dibangun, jumlah gedung sekolah baru, atau rasio guru-murid. Indikator-indikator itu penting, tentu saja. Tetapi indikator itu tidak pernah benar-benar merekam suara hati warga, aspirasi mereka, rasa frustrasi dan impian yang tersisa ketika pembangunan datang terlambat.
Selama beberapa dekade terakhir, Matraman telah dipandang sebagai daerah “cukup baik” dalam statistik, tetapi nyaris absen dalam dialog politik yang lebih luas. Mereka tidak pernah dianggap sebagai kantong kemiskinan ekstrem seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur, tetapi juga tidak dianggap strategis seperti kawasan Surabaya atau Malang Raya. Mereka berada dalam limbo pembangunan, di mana perhatian pemerintah datang seperlunya—umumnya saat pemilihan umum atau musim bencana.
Tanpa saluran ekspresi politik dan sosial yang berarti, warga Matraman melakukan apa yang dilakukan manusia ketika suaranya diabaikan: menciptakan ruang ekspresi sendiri. Mereka mungkin tak pernah membaca teori politik Hannah Arendt atau Antonio Gramsci tentang perlawanan sipil, tetapi secara naluriah, mereka tahu bahwa suara mereka adalah alat politik paling dasar dan penting. Ketika suara yang dianggap “tertib” tidak tersedia, mereka beralih ke suara yang dianggap “tidak tertib” sebagai satu-satunya cara menegaskan eksistensi.
Media nasional dan lokal cenderung melewatkan cerita ini. Mereka sibuk mengulas isu yang lebih “besar” seperti korupsi nasional, pemilu, atau pertumbuhan ekonomi. Media hanya akan melirik Matraman jika ada tragedi besar: kecelakaan lalu lintas, banjir bandang, atau perkelahian antarpendekar yang berujung maut. Padahal, peristiwa-peristiwa itu hanyalah gejala dari problem yang jauh lebih dalam—rasa frustrasi kolektif dari warga yang selama ini merasa tidak didengar.
Pada akhirnya, kita harus bertanya ulang tentang makna demokrasi kita. Demokrasi bukan sekadar pemilihan umum, bukan sekadar sidang parlemen, bukan hanya debat di layar televisi. Demokrasi sejati dimulai dari kemampuan untuk mendengar suara-suara yang tidak nyaman sekalipun. Ketika demokrasi gagal mendengar suara dari Matraman, maka demokrasi itu sendiri kehilangan sebagian maknanya.
Jika kita ingin suara-suara yang dianggap sebagai “kebisingan” ini mereda, maka cara terbaik adalah dengan membuka telinga kita lebih lebar. Mari mendengar apa yang ingin mereka katakan di balik suara mesin, teriakan pendekar, dan dentuman musik. Bagi masyarakat Matraman, suara mereka adalah suara tentang eksistensi. Mereka berteriak bukan sekadar karena ingin diperhatikan, tetapi karena mereka selama ini sudah terlalu lama berbicara pelan dan tidak pernah ada yang mau mendengar.
Di Matraman, knalpot brong, sound horeg, dan pendekar jalanan adalah demokrasi yang sedang berusaha berbicara—meski tanpa mikrofon, meski tanpa panggung resmi. Dan tugas kita sebagai bangsa adalah mulai mendengarkan. Sebab, suara mereka sama berharganya dengan suara-suara yang selama ini kita agungkan dalam pidato-pidato resmi kenegaraan. Mungkin bahkan lebih jujur.