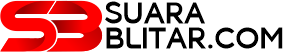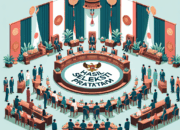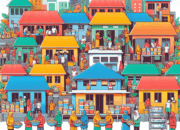Di tengah hingar-bingar kehidupan modern, istilah “sound horeg” menjadi sorotan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena ini? Sound horeg bukan sekadar tradisi lokal, melainkan sebuah pertunjukan suara yang kian populer dan kontroversial. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kita telah melihat pergeseran signifikan dalam cara sound system ini digunakan, yang berdampak pada ketertiban umum dan keharmonisan sosial.
Secara harfiah, sound horeg dapat diartikan sebagai suara yang menimbulkan getaran. Berasal dari istilah Jawa kuno, “horeg” berarti bergerak atau bergetar, yang mencerminkan karakteristik suara bertenaga yang dihasilkan. Awalnya, sound horeg digunakan untuk mengiringi berbagai acara besar, seperti takbiran, pengumuman publik, hingga kegiatan keagamaan. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya mengalami penyimpangan yang mengkhawatirkan.
Pengenalan sound horeg pertama kali muncul sekitar tahun 2014 pada pawai di Kabupaten Malang, dan sejak saat itu, popularitasnya menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Kini, sound horeg menjadi elemen penting dalam festival dan acara komunitas, namun tidak jarang menimbulkan masalah. Penggunaan sound system yang berlebihan dan di luar waktu yang wajar sering kali menyebabkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Tidak jarang, konflik sosial pun muncul akibat ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh suara yang menggelegar.
Tren sound horeg kini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ajang adu kekuatan antar komunitas. Fenomena ini banyak terlihat di kota-kota seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Malang, di mana istilah “masyarakat horeg” mulai dikenal. Mereka adalah kelompok yang rutin menggunakan sound system berdaya besar, menciptakan getaran yang dapat dirasakan hingga radius tujuh kilometer.
Sound horeg, meski menawarkan hiburan, juga membawa dampak negatif yang signifikan. Suara bervolume tinggi yang dihasilkan dapat mengganggu ketenangan lingkungan dan berpotensi menyebabkan kerusakan pendengaran bagi yang terpapar dalam waktu lama. Selain itu, getaran yang dihasilkan dapat merusak infrastruktur, seperti jembatan dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa, meski sound horeg berfungsi sebagai sarana pemersatu, keberadaannya sering kali dipandang sebagai polusi akustik.
Keberadaan sound horeg menimbulkan dilema. Di satu sisi, ia menjadi simbol kebersamaan dan keceriaan dalam berbagai perayaan. Namun di sisi lain, suara yang mengganggu dan dampak negatif yang ditimbulkan menjadi alasan bagi beberapa pihak untuk membatasi atau bahkan melarang penggunaannya.
Masyarakat kini dihadapkan pada pertanyaan penting: bagaimana kita dapat menjaga tradisi tanpa mengorbankan kenyamanan dan ketertiban? Sound horeg, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menjadi cermin dinamika budaya yang harus dikelola dengan bijak. Sebagai masyarakat modern, sudah saatnya kita menemukan keseimbangan antara merayakan tradisi dan menjaga lingkungan sosial yang harmonis.
Dengan memahami dan mengelola fenomena ini, diharapkan sound horeg dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang positif, bukan sekadar sumber masalah di tengah kehidupan masyarakat.