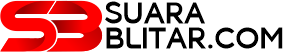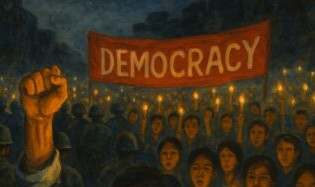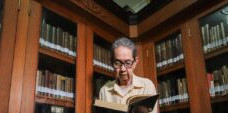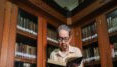Setiap Agustus, bendera Merah Putih kembali dipasang. Di halaman rumah, di perempatan jalan, di sudut-sudut yang selama sebelas bulan sebelumnya dibiarkan sepi. Warna itu adalah peringatan—bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang kewajiban untuk mengingat. Namun tahun-tahun belakangan ini, satu simbol lain mulai menyusup ke dalam ruang upacara dan euforia: bendera bajak laut. Ada yang memasangnya di motor, ada pula yang mengibarkannya di punggung saat karnaval. Lambang tengkorak dan tulang bersilang itu tampil sebagai tamu tak diundang di antara barisan siswa, drum band, dan ornamen bambu hias.
Sebagian orang menyebutnya tren. Yang lain menyebutnya penghinaan. Namun sebagian yang lebih tenang melihatnya sebagai gejala. Sebuah tanda bahwa kemerdekaan, yang dulu diperjuangkan dengan darah, telah kehilangan bentuk tetapnya. Ia mulai larut, mengendap dalam bentuk-bentuk simbolik yang absurd, ambigu, dan terkadang lucu. Di sinilah kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk menertawakan atau mengecam, melainkan untuk bertanya: mengapa simbol bajak laut begitu menarik bagi generasi yang lahir jauh setelah perang?
Bendera bajak laut, atau versi populernya dalam anime One Piece, bukan sekadar ikon hiburan. Ia adalah narasi yang hidup, tentang sekelompok orang yang menolak sistem, menjelajah lautan demi kebebasan, membentuk ikatan di luar hukum negara, dan mengejar harta karun yang hanya ada dalam legenda. Ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah mitos alternatif tentang kemerdekaan, tentang pemberontakan yang tidak ingin berakhir menjadi birokrasi. Dalam hal ini, One Piece lebih dari sekadar kartun Jepang. Ia adalah utopia anak muda yang lelah melihat nasionalisme berubah menjadi seremoni formal, korupsi rutin, dan pidato yang tidak menggerakkan siapa pun.
Mengibarkan bendera bajak laut di tengah perayaan kemerdekaan bukan bentuk perlawanan frontal. Itu bukan penolakan atas sejarah, melainkan keraguan atas bentuk-bentuk kekuasaan yang diwariskan. Mereka yang melakukannya tidak sedang membakar Merah Putih, mereka hanya bertanya dalam diam: “Apakah ini benar-benar kemerdekaan yang kalian maksud?”
Sosiolog mungkin akan melihatnya sebagai bentuk reframing, psikolog akan menyebutnya sebagai simbol perlawanan sublim. Namun di luar semua itu, kita menyaksikan bagaimana generasi baru sedang menulis ulang makna-makna lama dengan kosakata mereka sendiri. Mereka tidak membaca pidato proklamasi. Mereka menonton serial bajak laut. Dan di sanalah mereka menemukan versi kemerdekaan yang terasa lebih jujur, lebih relevan, lebih menantang.
Bisa jadi ini menunjukkan kegagalan negara dalam membangun imajinasi kolektif baru pasca-reformasi. Kurikulum pendidikan kehilangan kemampuan untuk menyulut api. Peringatan nasional lebih sering jadi proyek dekorasi. Narasi resmi tentang bangsa dan pahlawan terseret dalam protokoler dan promosi jabatan. Dalam ruang yang dingin itu, One Piece hadir sebagai dongeng yang hangat—tentang pertemanan, keberanian, dan impian yang tidak dikorupsi.
Namun tentu saja ini bukan berarti Merah Putih harus digantikan. Justru sebaliknya, ini ajakan agar Merah Putih tidak dibiarkan jadi lambang kosong yang hanya muncul di bulan Agustus. Bukan soal siapa lebih hebat antara pahlawan kemerdekaan dan kru Topi Jerami, tetapi tentang bagaimana dua simbol itu bicara pada zaman yang berbeda. Bendera bajak laut populer bukan karena ia asing, tetapi karena ia menjanjikan sesuatu yang semakin jarang kita temukan di dunia nyata: kebebasan yang terasa personal, hidup yang penuh risiko tapi bermakna, dan solidaritas yang tidak dicetak dalam bentuk kartu anggota.
Sebagian orang dewasa memprotes tren ini dengan marah. Mereka lupa bahwa generasi mereka pun tumbuh dengan tokoh seperti Gundala, Panji Manusia Milenium, atau kisah-kisah revolusioner yang dulunya juga dianggap “tidak sopan”. Waktu menguji semua simbol. Yang tidak luwes akan menjadi formalitas. Yang fleksibel akan terus hidup, bahkan jika ia berangkat dari dunia fiksi.
Hari kemerdekaan tidak harus menjadi museum beku. Ia bisa menjadi arena pertarungan tafsir, tempat simbol baru dan lama berdialog. Mungkin tugas kita bukan mengusir bajak laut dari panggung, melainkan bertanya kenapa mereka lebih dipercaya daripada pidato walikota. Dan dari situ, membuka ruang baru: untuk mendefinisikan ulang kemerdekaan—bukan hanya sebagai peringatan atas masa lalu, tapi juga sebagai percakapan tentang masa depan.
Kemerdekaan yang tidak dibicarakan akan menjadi seremoni. Kemerdekaan yang tidak dipertanyakan akan menjadi hiasan. Namun kemerdekaan yang didekati dengan imajinasi, humor, dan keberanian bertanya—ia punya peluang untuk hidup kembali. Mungkin itu sebabnya, di tengah barisan drum band dan pidato resmi, ada selembar kain hitam dengan tengkorak tersenyum. Ia tidak sedang menghina. Ia sedang mengingatkan. Bahwa di negeri yang katanya merdeka, masih banyak orang muda yang merasa harus membajak dunia agar bisa hidup seperti manusia.